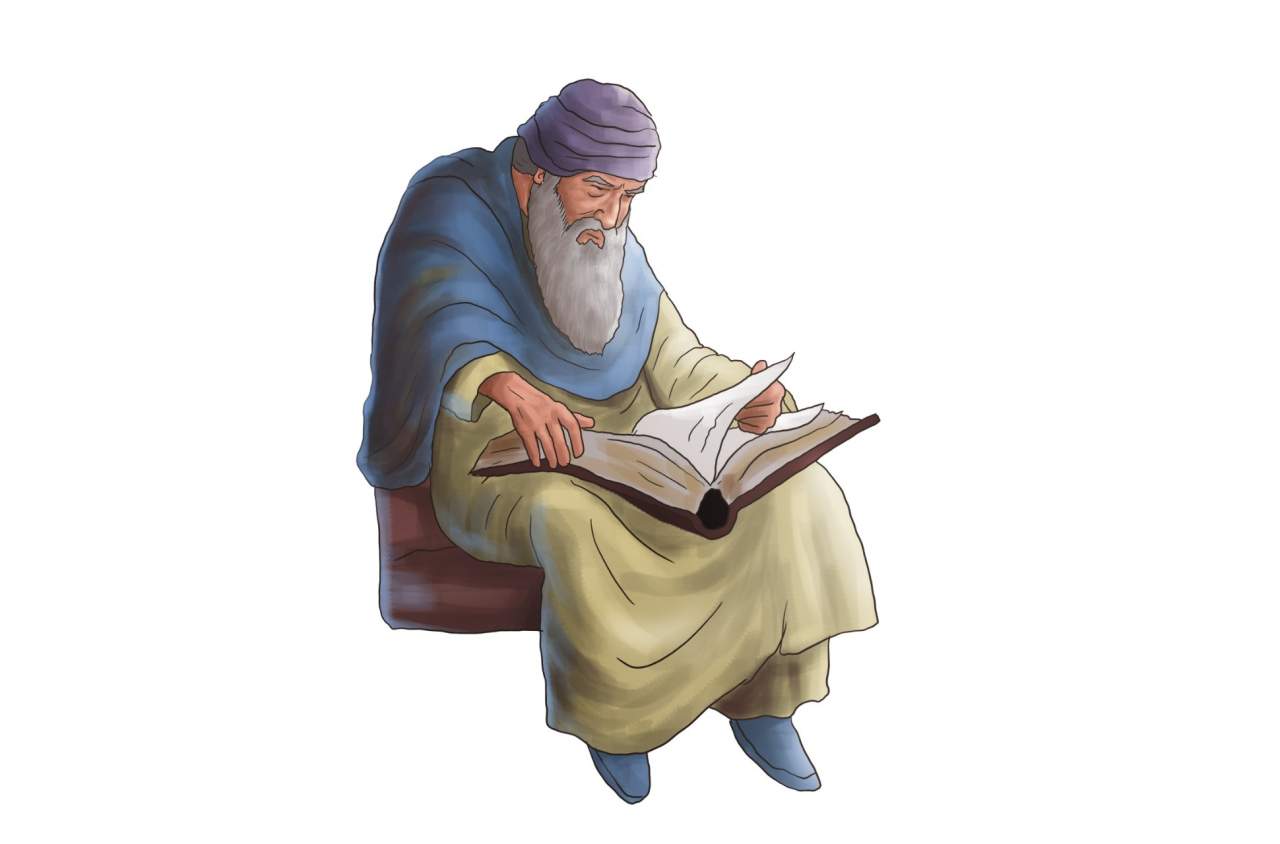(Dr. Hamdan Maghribi, M.Phil. — Dosen Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta)
Di hadapan arus modernisasi yang membawa serta kebangkitan gerakan puritanisme dalam Islam, tasawuf, dimensi spiritual yang telah menjadi jantung peradaban Islam selama berabad-abad, kini menghadapi tantangan besar. Berbagai kritik dan penolakan, yang secara umum dikenal sebagai anti-Sufisme, telah bangkit dengan argumen yang sistematis dan terstruktur. Fenomena ini bukan sekadar perdebatan teologis klasik, melainkan sebuah kontestasi ideologi yang meluas ke ranah politik, sosial, dan budaya. Esai ini akan mengupas tuntas mengapa anti-Sufisme menjadi isu sentral dalam Tasawuf Kontemporer, menelusuri akar sejarahnya hingga manifestasi terbarunya, dengan merujuk pada pemikiran para ahli.
Akar anti-Sufisme tidak muncul begitu saja di era modern. Ia memiliki jejak sejarah yang panjang, yang paling sering dikaitkan dengan pemikiran ulama abad pertengahan, Ibn Taimiyyah. Meskipun ia sendiri memiliki pengalaman spiritual dan mengapresiasi tasawuf otentik, Ibn Taimiyyah melancarkan kritik tajam terhadap apa yang ia lihat sebagai penyimpangan. Ia menolak praktik-praktik seperti ziarah kubur yang dianggap berlebihan, perantaraan (tawassul) kepada orang saleh, dan konsep-konsep mistik yang menurutnya tidak memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Bagi Ibn Taimiyyah, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berlandaskan syariat murni, yang ia sebut sebagai iḥsān. Kritiknya ini menjadi cetak biru (blue-print) bagi gerakan-gerakan reformis di kemudian hari, terutama yang berorientasi pada pemurnian akidah.
Dari Wacana ke Gerakan: Manifesto Anti-Sufisme
Pada abad ke-18 dan ke-19, gagasan Ibn Taimiyyah dihidupkan kembali dan disebarluaskan oleh gerakan-gerakan pembaruan. Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb di Semenanjung Arab dan Usman dan Fodio di Afrika adalah beberapa tokoh yang secara vokal menolak tradisi sufi yang dianggap mereka sebagai bid‘ah dan syirik. Mereka berpendapat bahwa praktik-praktik sufi telah menyebabkan kemunduran umat Islam karena menjauhkan mereka dari sumber-sumber otentik Islam dan membuat mereka pasif secara sosial-politik.
Di era kontemporer, anti-Sufisme tidak lagi terbatas pada lingkaran ulama, tetapi telah menjadi fenomena global yang tersebar melalui media massa dan internet. Meena Sharify-Funk, dalam bukunya Contemporary Sufism: Piety, Politics, and Popular Culture, menggambarkan kontestasi ini sebagai “perang wacana” yang menentukan otentisitas Islam. Para penentang tasawuf sering menggunakan media digital untuk menyebarkan narasi bahwa tasawuf adalah sebuah ancaman terhadap kemurnian akidah. Mereka menuduh tasawuf sebagai:
Sinkretisme (Takhayul, Bid‘ah, Khurafat): Tasawuf dituduh menyerap praktik-praktik non-Islam yang merusak akidah, seperti kultus individu terhadap syekh, kepercayaan terhadap karāmah (mukjizat), dan ritual yang dianggap tidak memiliki dasar tekstual.
Kepasifan Politik (Pasifisme dan Fatalisme): Tasawuf sering dituduh sebagai ajaran yang menjauhkan umat Islam dari tanggung jawab sosial dan politik. Hal ini dikarenakan fokus tasawuf pada pembersihan diri dan spiritualitas individu dianggap menciptakan mentalitas fatalistik yang tidak peduli pada masalah kemasyarakatan.
Ancaman terhadap Otoritas (Melawan Rasionalitas Fiqh): Para kritikus berpendapat bahwa pengalaman personal dan subjektif dalam tasawuf menempatkan otoritas spiritual di atas otoritas fiqh yang lebih objektif dan rasional. Hal ini dianggap merusak tatanan keagamaan yang mapan.
Neo-Sufisme: Rekonstruksi dari dalam
Di balik gelombang anti-Sufisme, muncul sebuah respons cerdas yang dikenal sebagai Neo-Sufisme. Gerakan ini bukan sekadar membela tasawuf dari serangan luar, melainkan melakukan rekonstruksi dari dalam. Neo-Sufisme menyadari bahwa beberapa kritik memang valid, dan bahwa tasawuf perlu dibersihkan dari praktik-praktik yang menyimpang untuk kembali ke akarnya.
Nursamad Kamba dalam Ke Arah Tasawuf Kontemporer menjelaskan bahwa Neo-Sufisme adalah upaya untuk mengembalikan tasawuf ke esensinya sebagai ajaran yang transformatif dan berbasis Qur’an dan Sunnah. Ia tidak menolak tasawuf secara keseluruhan, tetapi hanya menolak aspek-aspek yang menyimpang. Gerakan ini menekankan kembali pentingnya tasawuf sosial yang fungsional dan relevan dengan masyarakat. Konsep ini menentang gagasan bahwa tasawuf adalah ajaran pasif, sebaliknya, ia memandangnya sebagai sebuah kekuatan moral yang mampu mendorong keadilan sosial, empati, dan aktivisme.
Muzakkir juga mendukung pandangan ini. Ia memperkenalkan Tasawuf Qur’ani sebagai kerangka tasawuf yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Tasawuf Qur’ani menekankan pentingnya takhallī dan taḥallī dalam konteks masyarakat. Melalui pendekatan ini, tasawuf tidak lagi menjadi ajaran esoteris yang sulit dipahami, tetapi menjadi sebuah ilmu terapan yang dapat menjawab “kehampaan spiritual” dan “kekeringan jiwa” manusia modern. Ia mengajarkan bahwa mencari Tuhan tidak harus dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan memperbaiki hubungan kita dengan dunia dan sesama manusia.
Strategi Tasawuf Kontemporer dalam Menghadapi Anti-Sufisme
Untuk melawan narasi anti-Sufisme yang dominan, para pengusung tasawuf kontemporer telah mengadopsi beberapa strategi kunci:
Publikasi dan Komunikasi: Para akademisi dan praktisi tasawuf kontemporer, seperti yang tergambar dalam buku Muzakkir, kini aktif menulis dan mempublikasikan karya-karya yang menjelaskan tasawuf secara rasional dan populer. Mereka menggunakan media sosial, seminar, dan ceramah publik untuk menyebarkan pemahaman yang benar, melawan stereotip negatif, dan menyoroti relevansi tasawuf dalam isu-isu seperti Green Tasawuf (etika lingkungan) dan Gendering Sufism (peran perempuan).
Aktivisme Sosial: Tasawuf kontemporer menunjukkan relevansinya melalui kerja-kerja sosial nyata. Tarekat dan kelompok sufi modern tidak lagi hanya fokus pada zikir, tetapi juga terlibat dalam kegiatan amal, pendidikan, kesehatan, dan kampanye lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa tasawuf bukanlah ajaran yang pasif, melainkan sebuah jalan yang mendorong tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.
Integrasi dengan Ilmu Pengetahuan: Seperti yang dibahas dalam Menuju Arah Baru Studi Tasawuf di Indonesia, tasawuf kontemporer menggunakan pendekatan integrasi-transdisipliner. Ia berdialog dengan ilmu psikologi, sosiologi, dan bahkan sains modern untuk menjelaskan fenomena spiritualnya. Pendekatan ini menjadikan tasawuf lebih diterima oleh kalangan akademisi dan intelektual, yang sebelumnya mungkin skeptis terhadapnya. Konsep Rasa Ruhani oleh M. Iqbal Irham adalah contoh sempurna dari integrasi ini, di mana pengalaman spiritual dijelaskan dalam kerangka psikologis dan emosional.
Kontestasi Abadi antara Bentuk dan Substansi
Fenomena anti-Sufisme dalam konteks kontemporer pada dasarnya adalah perdebatan abadi antara bentuk dan substansi agama. Para kritikus anti-Sufisme, yang berfokus pada ketepatan ritual dan dogma, melihat penyimpangan dalam praktik-praktik sufi. Sementara itu, tasawuf, sebagai perwujudan iḥsān, menekankan pada substansi, yaitu kualitas batin dan penghayatan yang mendalam.
Tasawuf kontemporer tidak berusaha memenangkan perdebatan dengan cara retorika semata, melainkan dengan aksi nyata. Ia membuktikan bahwa spiritualitas sejati bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara untuk mengubah dunia dari dalam. Dengan membersihkan diri dari riya dan kesombongan, seorang sufi kontemporer dapat menjadi agen perubahan yang efektif, membangun masyarakat yang lebih berempati, adil, dan berkesadaban. Pada akhirnya, pertarungan antara anti-Sufisme dan tasawuf kontemporer adalah kontestasi tentang masa depan Islam itu sendiri: apakah ia akan menjadi agama yang kering dan formalistik, atau agama yang kaya akan spiritualitas, relevan dengan zaman, dan memancarkan kasih sayang ke seluruh alam.